Blak-blakan saja, saya tidak begitu tertarik menonton film-film Hollywod juga Indonesia, saya lebih suka film Indie atau film yang memang ditujukan bukan untuk komersil. Biasanya film-film begitu banyak titipan atau malah adegan yang dilebih-lebihkan. Tapi demi melihat Revalina S. Temat saat dijilbabi jadi malah tambah cantik, saya tertarik untuk menontonnya. Toh gratis, apalagi di hari pertama yang memang untuk kalangan terbatas juga untuk para jurnalis dan pekerja media.
Sumber: luqmanhakim.multiply.com
Buat saya PBS ini bukan film religi, meski memang mengangkat kehidupan Pondok Pesantren Al Huda di daerah Jombang, Jawa Timur, lengkap dengan prosesi kehidupan para kyai, ulama dan santri-santrinya.
Dikisahkan seorang perempuan kritis, Annisa (Revalina S. Temat), banyak bertanya tentang keberadaan perempuan dalam peranannya di dunia sekarang. Hidup di dunia yang sudah modern di format cerita setting tahun 1997, berkilas-balik ke kehidupan tahun 1985 saat kecilnya yang juga sudah kritis, mengalami banyak pergulatan pemikiran atas dominasi perempuan dalam kacamata Islam.
Annisa bukan Kartini yang membingungkan, Annisa juga bukan Che Guevara tokoh revolusioner legendaris, Annisa tetaplah Annisa yang digambarkan oleh Abidah sang penulis cerita sebagai sosok perempuan yang galau dengan peran pesantren menyikapi perempuan dalam sudut pandang keilmuan. Larangan banyak bertanya, sikap nurut dan manut perempuan dalam kultur pondok pesantren membuat tokoh cerita ini jadi terseok-seok menghadapi kehidupan. Semua yang direncanakan berjalan tidak mulus sesuai rencana.
Annisa yang jatuh cinta pada Chudori (Oka Antara) harus melepaskan cinta itu dan dinikahkan dengan Samsudin (Reza Rahardian), anak dari rekan ayahnya sesama Kyai. Adegan yang berlebihan, alur di awal yang hampir mirip sinetron-sinetron kebanyakan sempat membuat saya ingin muntah. Dulu saya pernah protes pada ceramah Shalat Jumat yang sempit dan tak universal. Aksi ini tentunya bikin jama'ah lain bingung, heran, aneh, bahkan kesal pada saya yang berani-beraninya mengkritik pengkhutbah Shalat Jumat. Baru setelah disadarkan oleh teman yang memang lebih mengerti, saya tinggalkan cara itu, paling kalau saya tak suka dengan ceramahnya, saya tinggal dan mencari masjid lain. Apalagi cerita di film ini, adegan di mana Annisa ditidakadilkan oleh Samsudin suaminya, Annisa yang dimadu, Annisa yang dipukul dan diperkosa oleh suaminya sendiri meski tak cabul cukup membuat saya berdiri dari bangku untuk segera meninggalkan gedung bioskop Planet Hollywood 21.
Saya tak suka alur cerita yang berlebihan, jauh dari dunia nyata meski itu jelas nyata dan ada di kehidupan. Tapi demi ingin mengambil intisari film ini, saya paksakan menonton sampai selesai. Di bagian tengah, Chudori yang pulang dari belajar di Al-Azhar, Kairo, Mesir dan bertemu Annisa, saya duduk tenang lagi di bangku. Chudori dengan karakter yang tenang bertemu Annisa yang tengah galau. Namun rasa ingin muntah itu datang lagi saat mereka dituduh berzina dan akan dihukum rajam. Alur yang tertebak, sama seperti Al-Masih saat membela pelacur yang akan dirajam, Nyai Muthmainah, Ibu Annisa (Widyawati) berdiri dan membela, "Siapa yang tak berdosa boleh merajam mereka!" Begitu katanya.
Alur terus bergulir dan saya pun kembali tenang lagi di bangku penonton. Adegan tentang setting Jokja dan kehidupan pondok pesantren meski saya tak pernah mondok, sempat membuat saya jadi sentimentil secara subyektif. Saat kecil saya terbiasa menjalani dua sekolah, pagi di SD Muhammadiyah dan siang sekolah di Ibtidaiyah, capek dan berat menjalani dua kehidupan begitu. Kakek saya dari ayah di Medan yang memang ulama sering menekankan prinsip-prinsip dasar Islam di keluarga. Pun kakek dari ibu yang aktivis Muhammadiyah sering mengajak saya kecil ke kantor PP Muhammadiyah di Menteng, membuat saya kecil sering terbengong-bengong melihat diskusi kakek dengan para tokoh Muhammadiyah kala itu, salah satu sahabat kakek saya adalah K.H. E.Z. Muttaqin yang namanya diabadikan jadi salah satu nama gedung di Unisba (Universitas Islam Bandung). Namun saat kedua kakek saya meninggal, saya jadi teringat fondasi dasar yang ditanamkan di keluarga. Saat menonton beberapa adegan yang memang mengkisahkan tentang pendidikan Islam, membuat saya beromantisme dengan kehidupan pendidikan Islam yang juga saya alami.
Islam itu mudah bukannya jadi bisa dipermudah. Islam itu rumit meski juga bukan untuk diperumit. Ada kesan memang di novel PBS Abidah El Khalieqy mencoba mendobrak tatanan baku kultur Jawa Islam dalam pondok pesantren memperlakukan perempuan. Abidah, beberapa situs yang saya browse banyak mengkritisi pemikiran-pemikirannya. Pun ada yang secara gamblang menjulukinya sebagai Feminis Rasis (klik ini). Tapi dari memilih judulnya saja saya sudah kagum. Arti di balik "Perempuan Berkalung Sorban" adalah perempuan yang memang menuntut kesetaraan dan egaliter. Sorban itu identik dengan laki-laki dalam khazanah kultur muslim, itulah yang diangkat oleh Abidah di novelnya.
Entah, saya belum membaca novelnya yang diterbitkan tahun 2000, belum bisa membandingkan plot film dan alur cerita novel. Tapi menontonnya saya relatif cukup menikmati, beromantisme sedikit dengan Jokja dan kehidupannya. Adegan membaca buku terlarang di masa Orde Baru, Bumi Manusia-nya Pramudya Ananta Toer sampai dibakar oleh para Kyai, saya punya romantismenya tersendiri. Saya membaca buku terlarang itu di Jokja juga buku-buku terlarang lainnya, dapat dari Shopping, salah satu daerah di belakang Benteng Vredeburg yang memang pusatnya banyak buku. Entah apa yang dilarang saya juga bingung, isinya bagus begitu kok dilarang pemerintah. Saya juga teringat salah satu aktivis di UGM yang kala itu mem-fotocopy buku Das Kapital-nya Karl Marx dan membuat kajian diskusi di Gelanggang Mahasiswa UGM. Diskusi belum selesai, meski cuma buku filsafat ekonomi, demi mendengar kata sensitif 'Karl Marx', semua peserta diskusi ditangkap dan dipertanyakan ideologi Pancasilanya. Si pem-fotocopy dan juga fasilitator diskusi ditangkap dan dipenjara 10 tahun. Sungguh masa-masa pembodohan bagi yang kuliah di jaman itu, pentutupan diri dari dunia luar dan takut akan segregasi ideologi.
Kelemahan detailnya mungkin pada mesin tik yang digunakan di tahun 1997. Okelah, buat yang pernah kuliah di Jokja masa-masa itu pasti tahu, meski komputer belum booming seperti sekarang tapi rental bertumbuhan bak jamur di mana-mana. Sedikit sekali yang memakai mesin tik. Khusnudzon saya mungkin tokoh cerita di sini adalah yang sedikit itu, tapi apa mungkin dengan setting LBH Yogyakarta tak ada komputer? Agak bingung juga, mungkin iya. Kalau iya, berarti kota tempat saya banyak belajar kehidupan ini terbelakang sekali dong! Tak usah juga bicara internet di tahun ini, belum ada. Tapi beberapa tahun kemudian di tahun 2000 awal, Jokja justru jadi pusatnya para hacker dan kota yang tergolong paling melek IT dan hebat dibanding kota-kota lain.
Saya relatif menikmatinya justru di bagian tengah dan akhir, saat di mana dengan kegigihannya Annisa menunjukkan diri bahwa perempuan juga bisa sama cerdas seperti laki-laki, namun ketergantungan pada laki-laki (yang baik tentunya) juga ada. Annisa yang begitu mencintai Chudori, sempat goyah saat suami keduanya yang tercinta meninggal tertabrak mobil. Sama persis seperti pandangan perempuan yang ditulis di buku 'Cinderella Complex', diangkat oleh Colette Dowling, dengan hal 'women's fear of independence', bahwa kodrat manusia, laki-laki dan perempuan memang saling mencintai, bahwa wanita juga punya ketakutan akan kemandirian.
Menonton film ini sesudahnya bisa juga ada sisi menyesal saya ke istri, di mana ketika baru menikah, istri saya yang (sepertinya) golongan Akhwat Fillah atau kalau Hassan Al Banna juga mendirikan Akhwatul Muslimat selain Ikhwanul Muslimin, istri saya yang (sepertinya) dari golongan itu jadi berubah 180 derajat. Saya yang tak berasal dari kalangan itu, saat itu yang gondrong, jeans dekil dan baju baju gambar tengkorak pernah dipandang tak enak oleh golongan ikhwan rekan istri saya. Awalnya masih bisa cuek lama-lama tak sabar, saya debati, saya pengen tau pola pemikirannya tentang Islam. Bila dulu saat baru menikah, istri saya pernah bilang kalau tak bisa memuaskan sebagai istri, saya sebagai suami boleh menikahi lagi. Saya kaget dan tak terbiasa dengan pola pemikiran yang melenceng dari egaliter, pun tak ada di keluarga saya yang poligami. Saya mengajaknya mencari dalil-dalil tentang perempuan di Islam, menunjukkannya bahwa perempuan itu memang punya hak dan kewajiban yang berbeda dengan laki-laki namun memiliki derajat yang tak kalah tinggi bahkan bisa lebih tinggi dari kaum Adam. Dalil yang menegaskan perempuan di bawah kendali suami itu kebanyakan dhaif dan dipertanyakan mutawatir juga sanad-nya. Kini istri saya kelewat mandiri dan sering mendebati, awalnya saya senang tapi lama-lama kewalahan. Ternyata saya masih egois, masih chauvinist bahwa laki-laki segalanya, he he he... Memang sudah seharusnya semua laki-laki membuang paham man chauvinism itu jauh-jauh bila ingin ada kesetaraan.
Itulah yang saya dapat dari film ini. Perempuan sebagai sosok revolusioner yang diwakili oleh Annisa. Seperti kata Subhan teman saya yang kita diskusi sedikit selesai menontonnya, film ini masuk kategori BO (Bimbingan Oelama), bilamana menontonnya dalam konteks yang sempit, kita akan menganggap bahwa Islam itu kaku, Islam itu jahat terhadap perempuan, padahal itu adalah potret kultur Jawa Islam dalam format kehidupan pondok pesantren. Jangan berharap iman akan menebal bilamana menonton film ini, bisa jadi malah sebaliknya, menuduh Islam itu tak humanis dan universal meski yang patut disalahkan adalah kulturnya, bukan agamanya. Makanya juga, "Perempuan Berkalung Sorban" ini saya katakan bukanlah film religi meski sarat kisah dengan bumbu Islam.
Mending nggak usah nonton sendirian kalo ujung-ujungnya dapat pemahaman yang tak jelas tentang Islam! Mintalah ditemani oleh Oelama, tentunya Oelama yang egaliter, Oelama yang universal dan humanis, bukan Oelama yang ada di puncak gunung dan membayangkan kehidupan dari kitab-kitab usang yang sudah menguning, tak sadar bahwa membaca Al Qur'an pun bisa dilakukan lewat HP...
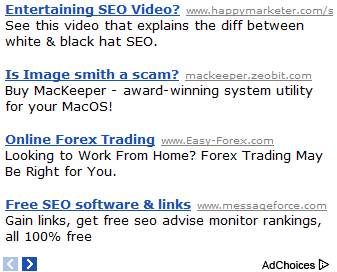
Tidak ada komentar:
Posting Komentar